Sastra Dan Politik: Apakah Sastra Berhubungan Dengan Politik?

BERBICARA tentang sastra tentunnya sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, karena karya sastra yang lahir di tengah-tengah masyarakat merupakan hasil imajinasi atau ungkapan jiwa. Sastra sebagai refleksi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Baik tentang kehidupan, peristiwa, maupuan pengalaman hidup yang telah dialaminya.
Dalam konteks umum, sastra tentunya sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Hal ini sejalan yang disampaikan Sumaryanto, ia mengungkapkan, bahwa karya sastra sebagai penjelmaan kehidupan akibat pengamatan sastrawan atas kehidupan sekitarnya.
Politik secara umum merupakan kesepakatan kolektif unuk kebijakan umum masyarakat. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sementara menurut Aristoteles, politik merupakan “master of science”, maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan, melainkan ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan.
Mengenai relevansi sastra dan politik, kita bisa merujuk pada konsep Gramsci mengenai dengan HEGEMONI SASTRA, bahwa teori sastra bisa menjadi wacana-wacana politik kekuasaan. Dalam ANALISIS WACANA, Gramsci mengungkapkan bahwa teks tidak berdiri sendiri, karena teks selalu berhubungan dengan legitimasi politik. Misalnya teks “Menangkan”. Teks ini bukan hanya sekedar kata, didalamnya menganduk makna yang besar, karena dalam teks politik terselubungnya kepentingan kekuasaan.
Teks (sastra) sebagai produk superstructure secara relatif tidak bergantung dengan base structure, teks memiliki otonomi relatif. Althusser menyebutkan bahwa teks sastra tidak lain adalah wacana ketaksadaran (unconsiousness) ideologis itu sendiri. Teks sastra merupakan transformasi dari proses tawar-menawar kehidupan individual dalam formasi sosial yang terjadi secara imajinari. Teks sastra sebagai praktik sosial terjadi berkat dan dalam ideologi. Dengan demikian, ideologi diartikan sebagai praktik-praktik yang dipercaya dan diyakini saling berhubungan dengan praktik, dan struktur kekuasan tempat menusia tersebut hidup.
Menurut Aprinus Salam, Mengungkapkan bahwa karya sastra diletakkan dalam satu kerangka representasi-representasi tentangan dalam kehidupan. Teori ini memiliki dan memberikan kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah stagnasi, tradisi, konflik dalam masyarakat, dan bagaimana praktik kekuasaan (politik) dioperasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori ini juga memberikan perhatian bagaimana “membongkar” karya sastra sebagai bagian dan satu hegemoni kekuasaan sehingga masalah “apa yang dikeluarkan (ekslusi)” dan “apa yang dimasukkan (inklusi)” sebuah karya sastra secara langsung berhubungan dengan konteks sosial dan politik masyarakat, yakni tempat karya sastra tersebut hadir.
Sastra tidak hanya mencerminkan realitas politik, tetapi juga mempengaruhi dan membentuk pandangan politik. Dari karya Shakespeare yang mengenai isu kekuasaan dan legitimasi hingga novel-novel dystopian seperti tahun 1984 George Orwell yang mengkritik totalitarianism. Artinya sastra bukan hanya dijadikan sebagai bahan merebut kekuasaan, tetapi, sastra juga menjadi bagian dari medium untuk mengomentari dan mereflekasikan realitas politik, karena sastra memiliki catatan sejarah berfungsi untuk memberikan wawasan tentang, norma, nilai dan politik.
Dengan demikian, karya sastra perlu diilhami dengan sungguh-sungguh agar kita dapat memahami dan menjadikan karya sastra sebagai refleksi untuk membela yang benar. Karena sejatinya, sastra bukan hnya sekedar untuk merebut kekuasaan, melainkan membela kemanusiaa.
“Sesulit apapun kehidupan ini, hiduplah hidup dengan damai” (*)

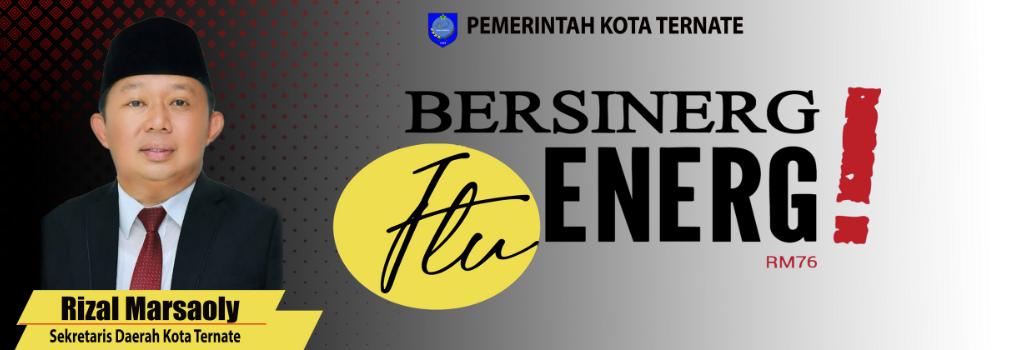








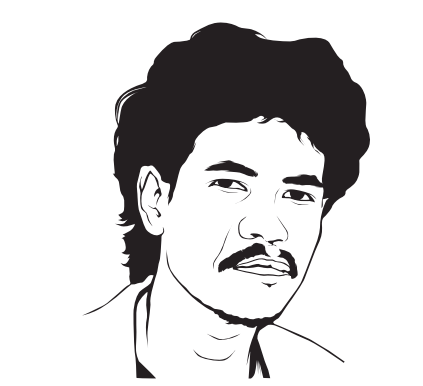
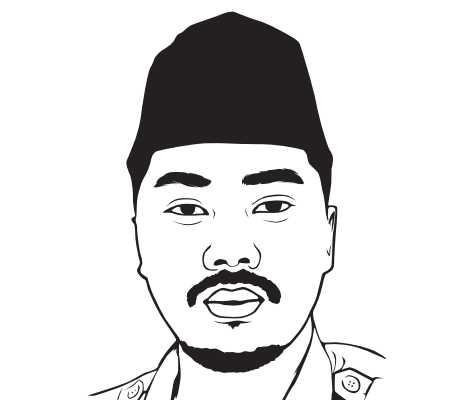


Komentar