Fetisisme Kecepatan

MALAM itu, setelah membaca buku Kebenaran dan Para Kritikusnya karya F. Budi Hardiman, saya duduk sendirian di depan kamar kos. Dua batang rokok Surya saya hisap perlahan, ditemani segelas kopi bon-bon racikan barista Caffe Bubula. Dari ponsel, lagu Someone Like You ciptaan Adele diputar pelan—cukup lirih, tidak mengusik keheningan, namun cukup menyejukkan bagi pikiran yang ingin merenung.
Di tengah kesejukan itu, saya mencoba mengingat kembali dan memaknai pikiran para filsuf atau para kritikus kebenaran yang dibahas Hardiman. Satu per satu saya tuliskan ke dalam catatan ponsel—entah yang benar-benar dipahami, atau yang hanya singgah sesaat di ingatan.
Setelah selesai, saya menggulir layer ponsel ke bawah, menyusuri catatan-catatan lama. Di sana, saya menemukan sebuah catatan yang saya tulis ketika berkunjung ke Desa Marituso Halmahare Selatan, saat mengawasi pemilihan kepala daerah. Dalam kunjungan itu, saya sempat berbincang dengan kepala desa — Abang Utam, begitulah beliau disapa, yang sementara duduk bersama warganya. Kami kemudian mengobrol sembari memantau proses pemilihan kepala daerah yang terus berlangsung.
Percakapan kami tidak panjang, tetapi padat. Saya mendengarkan dengan saksama ketika ia bercerita tentang hasil pemilihan legislatif sebelumnya hingga prediksi peta kekuatan dalam pemilihan kepala daerah saat itu. Namun dari semua yang ia sampaikan, ada satu kalimat sederhana yang membuat saya tertegun. Kalimat yang langsung saya abadikan dalam catatan ponsel: "Sesuatu yang diraih dengan muda itu berbahaya".
Malam itu, ketika membacanya kembali, kalimat tersebut memantik dorongan kuat untuk menuliskannya sebagai sebuah refleksi yang panjang. Bagi saya, ucapannya bukan sekadar nasihat, melainkan sebuah teguran yang menyadarkan—sebuah interupsi bagi kita yang hidup di zaman ketika “kecepatan” telah menjadi nilai baru peradaban. Dibalik gemerlap dan tawaran kemudahan yang disuguhkan zaman ini terdapat banyak paradoks yang begitu nyata. Dari sini kita dapat kembali bertanya: apakah kecepatan selalu menandakan kemajuan? Ataukah justru menjadi simbol keterasingan baru manusia modern?
FETISISME; Sebuah Ilusi Hasrat
Karl Marx dalam Kapital (1867) menjelaskan fetisisme ialah pemberhalaan akan benda ciptaannya. Dalam fenomena kekinian, yang disembah bukan lagi benda melainkan kecepatan. Kita menjadikan kecepatan sebagai ukuran kemajuan, kesuksesan, keberhasilan, efisiensi, juga kecerdasan. Tanpa kita sadari hal ini telah menjadi problem baru dalam keterasingan: manusia kehilangan waktu, proses, bahkan terasing bagi dirinya sendiri.
Seperti ditulis Erich Fromm, seorang psikolog jerman dalam bukunya "To Have or To Be?" (1976) bahwa masyarakat modern menjalani kehidupan dalam mode of having — mengejar hasil dan kepemilikan, bukan dalam mode of being yakni keberadaan yang sadar, hadir, dan bermakna. Dalam hal ini, menyembah kecepatan bukan budaya teknologi tetapi gejala eksistensi manusia. Dalam pandangan psikologis, kondisi ini menciptakan kecemasan eksistensial untuk selalu tampil maksimal, selalu bergerak, tanpa sempat berhenti mengenali diri sendiri.
Akibat dari perubahan paradigma baru ini, kecepatan seakan memiliki kesakralan. Kecepatan bukan lagi alat yang mengantarkan kita menuju kualitas — melainkan ia adalah tujuan itu sendiri. Kita tak lagi memperhitungkan nilai yang bermakna akan hasil yang didapatkan, namun terlena pada sensasi instan yang diberikan.
Kecepatan, Kelbatan, dan Kebermaknaan
Dewasa ini, kita disuguhkan dengan pelbagai kemudahan. Teknologi membuat aktivitas manusia menjadi efisien, jarak seolah lenyap, dan waktu terasa bisa dilipat. Namun di balik efisiensi itu, muncul budaya baru: manusia berlomba mengejar siapa yang paling cepat—kecepatan menjadi ukuran keberhasilan, bahkan ukuran nilai diri.
Fenomena ini merembes ke pelbagai ranah kehidupan manusia; dari ruang publik hingga ruang paling privat. Ia tidak mengenal batas status sosial: anak hingga dewasa, pengangguran hingga pejabat, mahasiswa hingga pengajar—semua terseret arus yang sama, arus kecepatan. Banyak dari kita tergoda oleh ilusi kekayaan instan, sebuah impian modern yang menjanjikan kemakmuran tanpa proses. Judi online menjadi “ruang baru” yang memfasilitasi fantasi itu: tempat meraih kemenangan tanpa perjuangan, ruang dimana logika kerja keras digantikan oleh keyakinan naïf, “aku klik, maka aku kaya.”
Padahal fenomena ini bukan semata-mata persoalan moral atau penyimpangan perilaku, melainkan ekspresi sosial dari kebutuhan psikologis manusia modern untuk menguasai waktu. Kita hidup dalam budaya yang memuliakan hasil seketika—yang membuat kesabaran dianggap usang. Kecepatan dipuja sebagai tanda kemajuan, sementara proses dilihat sebagai hambatan. Dalam lanskap mental semacam ini, kekalahan bukan hanya kehilangan uang, tetapi hilangnya kemampuan untuk menunda, menimbang, dan merasakan kehidupan yang lebih lambat.
Byung-Chul Han, filsuf kontemporer asal Korea, menyebut kondisi ini sebagai “kekerasan positif”—suatu bentuk kekerasan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dorongan internal untuk terus produktif, cepat, efisien, dan menguasai diri sendiri tanpa henti. Kita dipacu untuk melampaui batas, namun justru semakin terperosok ke dalam kelelahan kolektif. Di balik layar ponsel yang penuh notifikasi dan peluang instan, kita kehilangan ruang untuk diam, merenung, dan mengalami diri secara utuh. Kecepatan yang dahulu dipakai sebagai ukuran kemajuan kini berubah menjadi mekanisme penipisan makna; kita bergerak begitu cepat hingga tak lagi memiliki waktu untuk memahami ke mana kita sebenarnya menuju.
Dalam ritme hidup yang terus berpacu, kesunyian berubah menjadi sebuah kemewahan, dan kelambatan dipandang sebagai dosa sosial. Kita hidup dalam dunia yang mengukur nilai diri melalui kecepatan: semakin cepat seseorang bekerja, merespons, dan menghasilkan, semakin layak ia dianggap. Namun seperti diingatkan Viktor Frankl, manusia bukan sekadar makhluk yang berpikir—tetapi juga pencari makna. Dan makna, sebagaimana kebijaksanaan, tidak pernah muncul dalam ruang yang tergesa; ia tumbuh dari kesediaan untuk memberi waktu, memberi jeda, dan mendengarkan kehidupan yang berlangsung di dalam diri.
Carl Rogers (1961) menegaskan hal serupa ketika berbicara tentang pertumbuhan pribadi. Ia menyebut perlunya unconditional presence—kehadiran tanpa syarat, tanpa paksaan, tanpa dorongan untuk menjadi cepat atau sempurna. Dalam perspektif Rogers, perubahan yang otentik hanya dapat terjadi ketika seseorang diberi ruang untuk hadir sepenuhnya pada dirinya sendiri, tanpa tekanan eksternal untuk segera “menjadi” sesuatu. Artinya, transformasi tidak lahir dari kecepatan, melainkan dari proses internal yang berjalan dengan kehendaknya sendiri.
Dalam “lambat”, manusia menemukan kesempatan untuk melihat dirinya dengan jernih. Kelambatan bukan penundaan, melainkan praktik kesadaran: sebuah ruang di mana seseorang dapat membedakan kehendak diri dari tuntutan sosial, suara batin dari kebisingan luar. Justru dalam momen-momen itulah manusia menyadari bahwa ia bukan sekadar entitas yang bergerak mengikuti paradigma luas, tetapi subjek yang memiliki kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri.
Memaknai Ulang Proses
Untuk keluar dari fetisisme kecepatan, kita perlu memulihkan cara pandang terhadap proses. Proses adalah ruang dimana manusia bertransformasi. Ia merupakn wilayah di antara niat dan hasil—tempat di mana kesadaran tumbuh, kesabaran diuji, dan makna ditemukan. Kita mungkin perlu belajar kembali pada sesuatu yang perlahan: pada air yang sabar mengikis batu, pada benih yang bertumbuh di tanah, pada malam yang memberi ruang bagi renungan. Dalam dunia yang menuhankan kecepatan, kelambatan adalah bentuk perlawanan.
Memaknai ulang proses berarti menolak reduksi diri menjadi mesin efisiensi. Artinya, kita belajar kembali menilai perjalanan, bukan sekadar hasil. Dalam kelambatan, ada ruang untuk kesadaran; dalam jeda, ada kesempatan untuk memahami arah; dalam proses, ada kemungkinan untuk menjadi utuh.
Kita tak perlu menolak kemajuan, tetapi perlu menata ulang hubungannya dengan makna. Teknologi seharusnya membantu manusia menjadi lebih sadar, bukan lebih terburu-buru. Maka, mungkin benar apa yang dikatakan Abang Utam di hari itu: “Sesuatu yang diraih dengan mudah itu berbahaya.” Karena di antara yang cepat dan yang lambat, manusia modern sedang diuji: apakah ia memilih menjadi efisien, atau menjadi bermakna. (*)

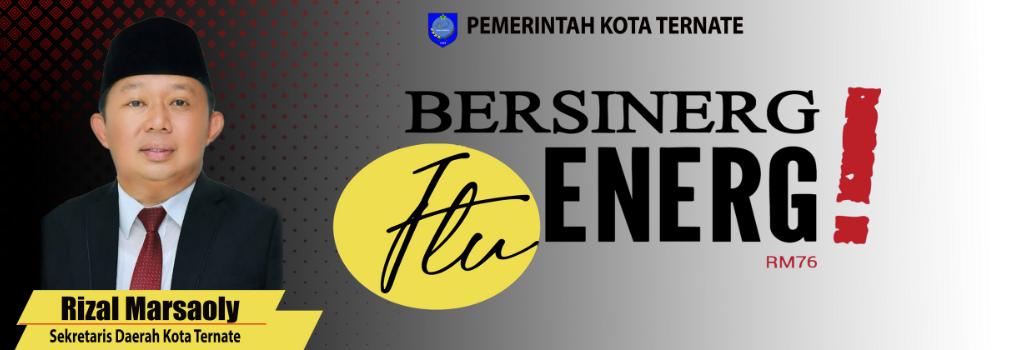








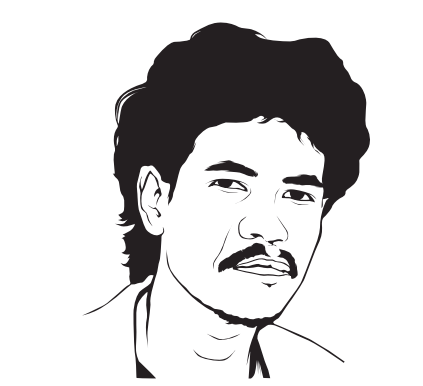
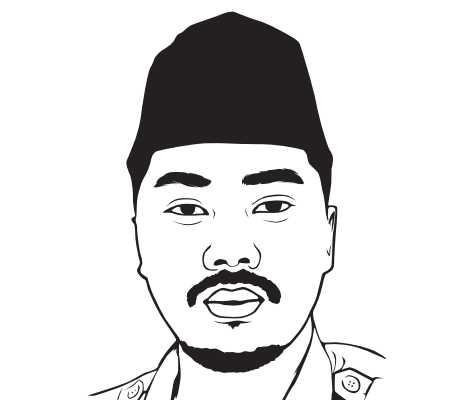


Komentar