Ketika Negara Jadi Kerajaan Nepotisme Modern

Kedua, kelemahan mekanisme akuntabilitas membuat praktik itu sulit dihentikan. Ketika pengawas internal lemah, hukum tentang konflik kepentingan samar, dan lembaga penegak hukum mudah diintervensi, celah itu dimanfaatkan.
Praktik politik yang menempatkan loyalitas di atas kompetensi juga memupuk budaya bahwa posisi publik adalah hadiah politik, bukan amanah publik. Dalam konteks ini, meritokrasi tergerus, dan kompetensi menjadi korban ritual pengangkatan yang diwarnai kepentingan kekerabatan.
Dampaknya nyata: alokasi sumber daya yang suboptimal, layanan publik yang timpang, dan berkurangnya kesempatan ekonomi bagi pelaku usaha yang bukan bagian jaringan elite.
Ketika proyek besar dipilih bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat melainkan kepentingan politik, hasilnya terasa di sekolah yang kurang sarana, puskesmas yang tak memadai, jalan yang amburadul, meskipun pada kertas anggaran terlihat ‘modal’ pembangunan.
Lebih parah lagi, ketika warga menyaksikan favoritisme berulang, partisipasi politik menurun; masyarakat menjadi apatis atau sinis terhadap proses demokrasi. Ini bahaya panjang bagi masa depan republik.
Lalu, mengapa wacana publik kadang tak cukup efektif menahan praktik ini? Karena elite memiliki kapasitas untuk mereformulasikan narasi: nepotisme disamarkan sebagai ‘kontinuitas’, oligarki dilukiskan sebagai ‘stabilitas’, dan tindakan yang menguntungkan kelompok tertentu dibalut bahasa pembangunan.
Media yang kuat dan investigatif penting tapi tanpa perlindungan hukum untuk kebebasan pers dan whistleblower, serta tanpa penguatan lembaga pengawas yang independen, narasi-narasi itu terus mengendapkan praktik-praktik lama.
Apa yang harus dilakukan? Pertama, reformasi aturan konflik kepentingan harus diprioritaskan: pengungkapan aset yang ketat, larangan langsung bagi pejabat untuk menunjuk keluarga dalam posisi strategis, dan sanksi yang jelas ketika penyalahgunaan terjadi.
Baca Halaman Selanjutnya..

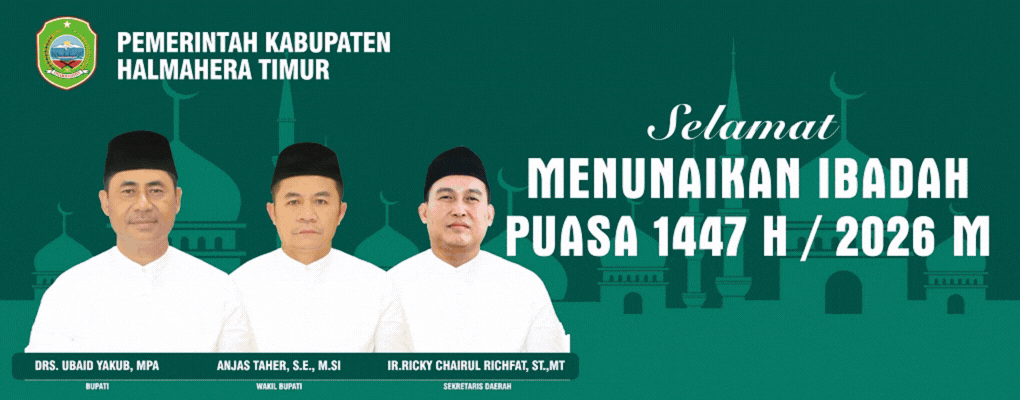













Komentar