Wajah Umum Masyarakat Malut Sebagai Wilayah Pertambangan
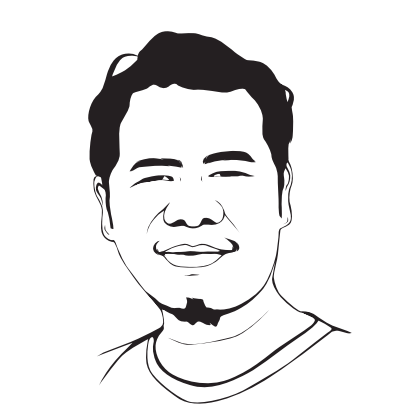
Ruang hidup mereka direnggut, tanah direbut, air tercemar. Kata “pembangunan” justru melilit kebebasan mereka, hingga sejarah dan ruang hidup lama tergilas oleh kepentingan baru yang asing bagi mereka.
Kemungkinan Lain
Pernyataan Menteri Muhadjir Effendy cukup menohok: “Maluku Utara banyak tambang, tapi masyarakat miskin.” Seharusnya, kata beliau, tidak ada lagi masalah stunting, rumah tidak layak huni, atau krisis air bersih di daerah sekaya Maluku Utara. Jika masih ada, berarti ada yang tidak beres.
Kekayaan tambang semestinya dinikmati rakyat Maluku Utara terlebih dahulu. Pemerintah harus memastikan perusahaan tambang menyalurkan manfaat CSR (Corporate Social Responsibility) untuk program pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, dan layanan dasar lain. Namun, CSR sering hanya sebatas bantuan jangka pendek, padahal mestinya berkelanjutan.
Selain itu, soal pembagian hasil tambang juga penting. Kabupaten atau kota penghasil tambang seharusnya mendapat porsi lebih besar dibanding daerah lain, agar kesejahteraan masyarakat lingkar tambang benar-benar tercapai.
Namun, semua itu akan kembali pada distribusi dan keadilan ekonomi. Apakah mungkin keadilan hadir di tangan oligarki? Manusia, kata Marx, memiliki dua dorongan dasar: dorongan tetap (seperti lapar dan hasrat biologis) serta dorongan relatif (dibentuk oleh kondisi sosial-ekonomi).
Dalam sistem kapitalistik modern, kebutuhan akan uang bukan lagi kebutuhan alami, melainkan kebutuhan yang diciptakan. Dari sinilah lahir kerakusan, oportunisme, dan perebutan kepentingan.
Penutup
Akhirnya, cerita umum, dilema umum, dan kemungkinan lain saling berebut makna. Semua bertemu dalam pertanyaan besar: akankah wajah masyarakat Maluku Utara sebagai wilayah tambang benar-benar menuju kesejahteraan? Atau hanya akan tetap menjadi mitos kemakmuran yang sulit diwujudkan? (*)

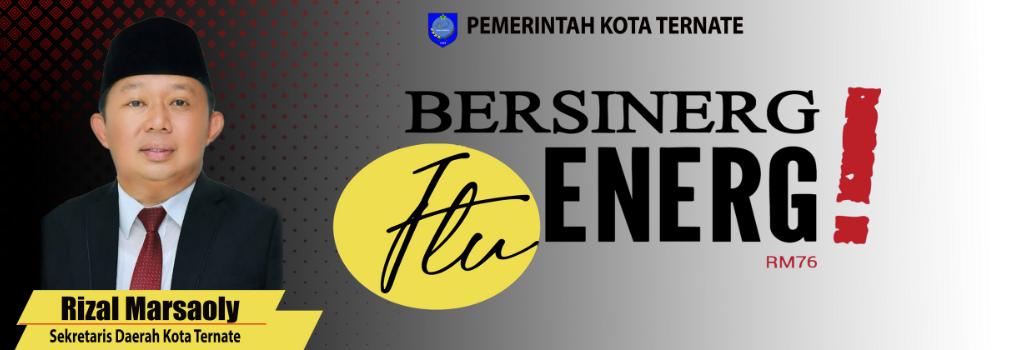












Komentar