Di Balik Nikel: Mitos Kesejahteraan dan Realitas Penderitaan

INDONESIA hari ini dielu-elukan sebagai “rajanya nikel” dunia. Narasi ini tidak tiba-tiba muncul dari ruang kosong, akan tetapi berdasarkan fakta obejktif. Data United States Geological Survey (USGS) menunjukan bahwa Indonesia di tahun 2024 memproduksi 2,2 juta ton biji nikel. Ini sekaligus menghantarkan Indonesia sebagai rangking satu produksi nikel dunia, kemudian disusul oleh Filipina pada urutan kedua. Bahkan oleh Badan Geologi Sumber Daya Nikel Indonesia memperkirakan negara ini memiliki cadangan nikel mencapai 11,7 miliar ton yang terkonsentrasi di dua wilayah, yakni Sulawesi dan Maluku Utara.
Di atas kertas, data dan angka ini terlihat begitu sempurna. Nikel adalah primadona di era modern, bak rempah cengkeh dan pala di beberapa abad lalu. Jika kekayaan sumber daya alam ini dikonversi menjadi kekuatan ekonomi, maka APBN akan mendapatkan tambahan devisa yang besar. Namun realitasnya justru berbanding terbalik. Alih-alih mewujudkan kesejahteraan, tambang nikel justru acapkali menyisahkan ironi kepada masyarakat lokal. Perampasan ruang hidup dan kerusakan ekologi menjadi fenomena yang kerapkali kita temukan di berbagai wilayah pertambangan. Tak terkecuali pada dua wilayah yang telah penulis sebutkan di atas.
Janji Kesejahteraan
Kesejahteraan yang digaungkan pemerintah tak lebih dari sekedar narasi kosong, sebab kontras dengan relitas di basis masyarakat. Pemerintah menyatakan skema hilirisasi mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan membuka banyak lapangan pekerjaan. Akan tetapi dunia kerja perburuhan di industri nikel ini masih diwarnai dengan angka kecelakaan kerja yang tinggi. Laporan Sengkarut Perburuhan Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) oleh Rasamala Hijau Indonesia dan Trend Asia menunjukan adanya kesemrautan sistem kerja yang dialami buruh IMIP. Faktanya, masih ada perekrutan yang tidak transparan, fleksibilitas mutasi buruh, instabilitas kontrak kerja, hingga sistem kerja yang memaksa untuk mengambil lembur agar menerima upah layak. (Trend Asia, 2024).
Di Maluku Utara, memang beberapa tahun terakhir ini mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sebagaimana rilisan Badan Pusat Statistik (BPS) Malut, menunjukan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada kuartal II 2025 sebesar 32,09 persen, dengan motor utamanya adalah sektor industri dan hilirisasi. Meski demikian, presentase ini tidak bisa menjadi dalil untuk mengatakan rakyat Maluku Utara telah sejahtera. Justru lonjakan pertumbuhan ekonomi ini, kontras dengan angka kemiskinan di Maluku Uatara. Dalam rilisan BPS Malut, pada tahun 2024 angka kemiskinan di dua kabupaten yakni Halsel dan Haltim, kini masih bertengker di posisi satu dan dua tertinggi dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Padahal, Halsel dan Haltim adalah daerah industri pertambangan yang akrab dengan narasi-narasi kesejahteraan. Fakta ini menunjukan sebuah ironi bahwa tinggi pertumbuhan ekonomi hanyalah angka yang tak berarti apa-apa bagi masyarakat kelas bawah.
Mitos kesejahteraan acapkali dibangun lewat retorika ekonomi-politik. (Ardianto, 2016: 72) menggambarkan bagaimana skema pemerintah dalam menciptakan mitos sosial (social myths) berupa “tambang demi kesejahteraan”. Mitos ini lahir dari dekonstruksi makna kemiskinan oleh pemerintah. Bahwa kemiskinan sebagai krisis mesti diselesaikan dengan menghadirkan pertambangan skala besar sebagai solusi. Dengan begitu, negara dengan mudah mendistraksi rakyat bahwa industri-industri ini kelak akan menjadi solusi bagi lapangan kerja baru. Padahal justru realitasnya, lapangan kerja itu akan menjadi arena eksploitasi terhadap tenaga kerja buruh.
Realitas Penderitaan di Lapangan
Penderitaan akibat operasi pertambangan nikel di Indonesia sangat signifikan. Dampak pertambangan nikel yang merusak ekosistem di daerah pesisir pantai berimplikasi pada krisis ekologis dan ketahanan pangan masyarakat lokal.
Sebagai contoh; kehadiran PT. IMIP dengan hasil limbah yang merusak telah mematahkan sumber pencaharian masyarakat lokal yang yang bergantung pada sektor laut dan perikanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, akibat dari limbah tambang nikel yang merusak terumbu karang dan jenis biaota laut lainnya, kini masyarakat lokal di pesisir Morowali menempuh jarak yang lebih jauh untuk menangkap ikan. (Syarifuddin, 2022: 19-23).
Di Maluku Uatra, penelitian yang dilakukan Pusat Studi Akuakultur Unkhair Ternate menemukan adanya kontaminasi kadar logam berat dalam ikan dan kerang yang telah melebihi batas normal. Bahkan dampak pertambangan nikel di Pulau Obi juga telah mempengaruhi kesehatan warga. Mereka kerap jatuh sakit dengan keluhan gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh polusi PLTU batubara dari aktivitas tambang (Saputra, dkk, 2023: 83). Belum lagi degradasi lahan pertanian akibat deforestasi hutan juga memperpanjang penderitaan masyarakat lokal yang basis ekonominya adalah petani.
Fakta penderitaan juga dialami oleh petani padi Dusun Woejerana, Weda Tengah, yang berada dekat dengan wilayah konsesi pertambangan PT. IWIP dan PT. WBN. Mengutip rilisan mogabay.co.id per tanggal 01/05/2023, menunjukan bahwa pada tahun 2021 petani Woejerana mengalami gagal panen akibat banjir bandang yang merusak padi siap panen sekaligus lahan pertaniannya. Yang paling mencengangkan, hasil penelitian Nexus Foundation dan Universitas Tadulako tahun 2025. Dalam penelitian ini membeberkan fakta bahwa darah masyarakat lingkar tambang di Halteng telah terkontaminasi merkuri dan arsenik yang telah melewati batas aman.
Lambat laun, gelombang kasus penyakit yang dialami masyarakat Jepang akibat limbah kadium yang dibuang ke Sungai Ziju (Diamond, 2017: 594) juga akan terjadi pada masyarakat di berbagai daerah pertambangan di Indonesia.
Sementara luka kerusakan yang ditinggalkan akibat eksploitasi sumberdaya alam dan penghisapan tenaga buruh berlebihan dengan maksud untuk mengejar target produksi (cenderung over) ini, justru membuahkan hasil penurunan harga nikel di pasar global. Pada tahun 2023 harga nikel rata-rata tahunan menurun hingga 15 persen, diabandingkan dengan tahun 2022. Penyabab utamnya adalah surplus nikel (oversupply) dari Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan harga nikel hingga akhir tahun 2023. Jika melihat data dari tradingeconomics harga nikel globar turun sampai menyentuh angka USD 15.000 per ton, angka ter rendah dalam beberapa tahun sebelumnya. (Putri, & Ayyubi, 2024: 7-8).
Jika ini terus berlangsung, maka hanya soal waktu, harga nikel itu akan semakin tertekan di pasar internasional. Berdasarkan analisis World Bank Commodity Market Outlook pada tahun 2022, dengan mengamati kondisi tersebut, harga nikel diperkirakan akan terus mengalami penurunan, dengan estimasi penurunan sekitar 16 persen sejak tahun 2023. (Nisaa, 2023).
Ironi Keadilan dan Masa Depan.
Deretan fakta dan luka di atas adalah bagian kecil dari dinamika industri nikel Indonesia. Narasi “mitos kesejahteraan” telah sekaligus memberikan pesan tersembunyi bahwa di negeri para bedebah ini, keadilan hanyalah ironi.
Perjuangan menuntut keadilan atas hak hidup yang nyaman diatas tanah yang subur berujung pada kriminalisasi bukan lagi fenomena yang langkah ditemui. Kasus 11 warga Maba Sangaji dan banyak kasus-kasus lain adalah cerminan bahwa keadilan dalam kenyataannya masih jauh dengan apa yang kita harapkan. Kini para pejuang lingkungan itu masih mendekam di penjara dengan segala ketidakpastian; antara bebas atau mendekam lebih lama.
Dari sini semakin kontras terbaca, dibalik pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ternayata dibayar mahal oleh kerusakan dan penderitaan rakyat Maluku Utara. Sedangkan yang menikmati hanyalah para “bandit-bandit” yang senantiasa mendalilkan bahwa tambang adalah solusi untuk menuju kesejahteraan. Tentu diantara kelompok itu termasuk orang nomor satu di Maluku Utara saat ini. Paling tidak, ia dibanjiri pujian oleh “bandit-bandit” Jakarta.
Dari semua itu, ada pertanyaan yang kemudian muncul; apakah nikel benar-benar membangun masa depan? Atau justru menggadaikannya? Atas pertanyaan ini kita menemukan jawaban bahwa nikel bisa jadi berkah, tapi selama mitos kesejahteraan menutupi realitas penderitaan, ia tak lebih dari kutukan baru. Dan jika yang sadar berhenti untuk melengkingkan suara dan berjuang, maka seperti judul buku yang ditulis David Wallace, manusia hari ini hanya akan mewariskan ‘bumi yang tak dapat dihuni’ lagi.(*)

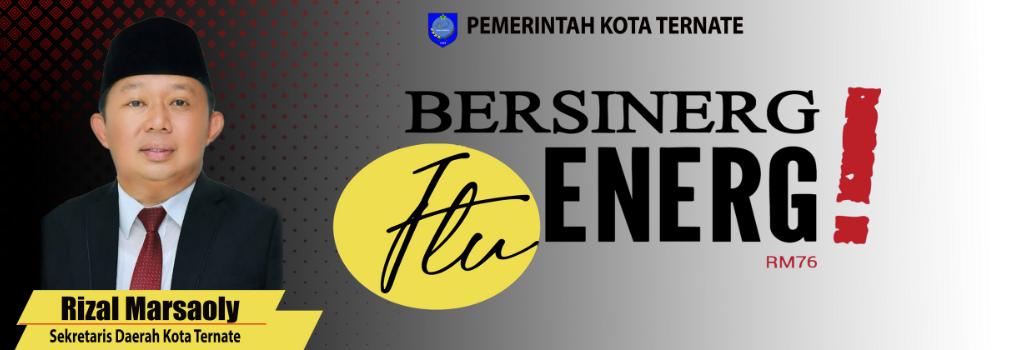












Komentar