Banjir, Relasi Kuasa dan Anthropologi

Terlepas dari perbedaan data laju deforestasi antara versi pemerintah dan versi lembaga lingkungan (WALHI misalnya), secara keseluruhan kondisi deforestasi makin mengkhawatirkan.
Dari sudut pandang antropologi sosial, deforestasi dan dampaknya berupa bencana banjir bukan sekadar persoalan hitung-hitungan angka (data) dan teknis hidrologi atau tata ruang, melainkan cerminan dari hal yang lebih substantif yaitu rusaknya relasi sosial antara manusia, alam, dan kekuasaan.
Hutan sebagai Ruang Sosial
Dalam perspektif antropologi, hutan tidak pernah dilihat sekadar sebagai kumpulan pohon dan ekosistemnya. Banyak komunitas lokal dan masyarakat adat menjadikan hutan sebagai ruang hidup.
Hutan sebagai sumber pangan, sistem nilai, pengetahuan lokal, dan identitas. Di dalam hutan, mereka membangun relasi timbal balik dengan mengambil seperlunya, merawat keseimbangan, dan mewariskan pengetahuan dan kearifan lingkungan secara lintas generasi.
Namun, ketika negara dan korporasi memandang hutan semata sebagai “lahan bisnis” atau “cadangan sumber daya”, makna sosial budaya dan ekologis tersebut dimarjinalkan, tersingkir, dan bahkan terhapus.
Hutan direduksi menjadi komoditas. Dalam konteks pertambangan mineral seperti batu bara, nikel, bauksit, emas, dan juga dalam konteks perkebunan skala besar (sawit misalnya), hutan dilihat sebagai penghalang yang harus disingkirkan demi efisiensi produksi.
Hasil dari cara pandang ekstraktif terhadap hutan bukan hanya fisik ekologis, tetapi juga penghancuran relasi sosiobudaya antar manusia dengan lingkungannya yang telah lama merawat keseimbangan ekologi lokal. Ketika relasi ini rusak, yang tersisa adalah lanskap rapuh tanpa mekanisme sosial untuk merawatnya.
Baca Halaman Selanjutnya..

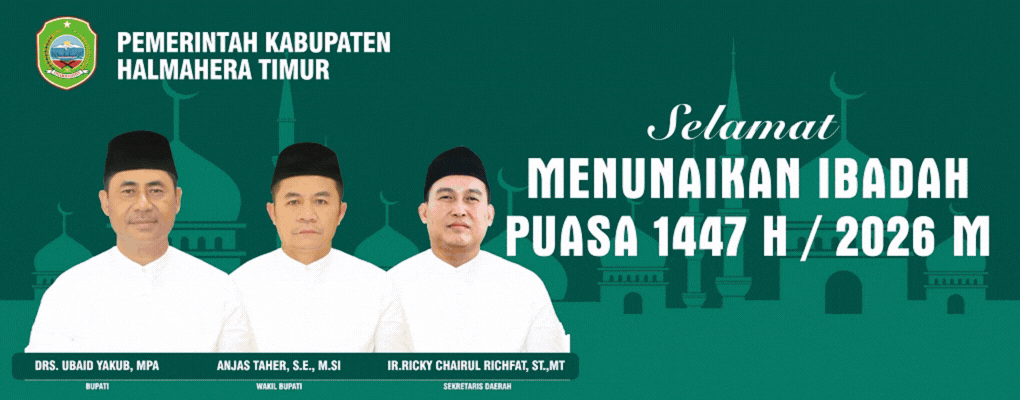













Komentar