Energi untuk Siapa? Kritik atas Perampasan Lahan Petani di Halmahera Barat dalam Bayang Kapitalisme Hijau

ISU energi terbarukan menjadi wacana global yang paling banyak diangkat pada dekade terakhir. Dunia berlomba-lomba mencari solusi atas krisis iklim dan ketergantungan terhadap energi fosil. Dalam arus besar tersebut, Indonesia menempatkan energi panas bumi (geotermal) sebagai salah satu sumber energi utama yang disebut-sebut ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, di balik narasi yang tampak progresif itu, muncul persoalan mendasar yang menuntut refleksi kritis: energi untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dilakukan?
Pertanyaan tersebut menemukan relevansinya di Halmahera Barat, Maluku Utara, di mana proyek pengembangan energi panas bumi justru menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Masyarakat petani dan adat yang selama ini hidup dari tanah dan sumber daya alamnya harus berhadapan dengan korporasi besar yang membawa nama pembangunan nasional dan “energi hijau”. Luas lahan yang dibutuhkan dari pembangunan geotermal yang ada di Halmahera Barat mencakup 13.580 hektare yang mencakup dua kecamatan yang ada yakni adalah kecamatan Jailolo selatan dan kecamatan Sahu.
Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Henry Bernstein (2001) sebagai bentuk baru dari ekspansi kapitalisme global yang kini menyusup melalui proyek-proyek lingkungan. Kapitalisme yang dulu dikenal eksploitatif kini berganti wajah menjadi kapitalisme hijau — sistem ekonomi yang menggunakan narasi keberlanjutan untuk melegitimasi perampasan sumber daya alam dan tenaga manusia di negara-negara pinggiran. Esai ini berupaya menyoroti dinamika tersebut dengan menempatkan kasus Halmahera Barat sebagai cermin dari kontradiksi antara pembangunan hijau dan keadilan sosial.
Kapitalisme Hijau: Wajah Baru Eksploitasi
Dalam teori ekonomi politik kritis, kapitalisme selalu beroperasi melalui logika akumulasi tanpa batas—memperluas wilayah produksi dan mengekstraksi nilai dari sumber daya yang sebelumnya belum dimasuki pasar. Henry Bernstein dalam Class Dynamics of Agrarian Change (2010) menegaskan bahwa kapitalisme modern terus memperluas cakupan produksinya dengan mengintegrasikan ruang-ruang agraris ke dalam sistem ekonomi global. Proses ini tidak selalu berlangsung melalui kekerasan fisik, tetapi lewat mekanisme hukum, kebijakan, dan wacana pembangunan.
Dalam konteks kontemporer, kapitalisme menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Krisis lingkungan yang semakin parah dijadikan alasan baru untuk membuka pasar-pasar baru: energi bersih, perdagangan karbon, dan proyek “sustainability”. Maka lahirlah istilah kapitalisme hijau — sebuah ironi di mana alam dieksploitasi untuk “diselamatkan”.
Narasi kapitalisme hijau beroperasi secara halus: ia menjanjikan pembangunan berkelanjutan, pengurangan emisi, dan kesejahteraan rakyat. Namun, di lapangan, yang terjadi justru kebalikan. Energi hijau tidak lepas dari logika ekonomi politik yang sama: menempatkan masyarakat lokal sebagai objek, bukan subjek; menjadikan alam sebagai sumber komoditas baru; dan mengkonsentrasikan keuntungan pada segelintir aktor negara dan korporasi.
Halmahera Barat: Ketika Tanah Petani Menjadi Korban “Pembangunan Hijau”
Halmahera Barat, bagian dari gugusan kepulauan Maluku Utara, memiliki potensi panas bumi yang besar karena berada di wilayah vulkanik aktif. Sejak awal 2010-an, pemerintah dan beberapa perusahaan energi telah melakukan survei dan eksplorasi di sekitar Kecamatan Jailolo dan Ibu. Proyek ini dimasukkan ke dalam program nasional transisi energi, didukung oleh investasi dalam dan luar negeri.
Namun, di balik euforia pembangunan energi bersih, muncul realitas pahit bagi masyarakat lokal. Lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka berubah fungsi menjadi area industri energi. cengkeh, pala, kelapa, dan hutan tempat mereka menggembala dan berburu perlahan hilang. Sebagain masyarakat kini memilih dan membiarkan lahan mereka dipatok untuk masuk dalam area eksplorasi geotermal dengan iming-iming kesejahteraan kedepan terkait lapangan pekerjaan.
Hal ini dapat membuat masyarakat jauh dari tanahnya dan akhirnya memilih untuk menjadi buruh kasar dalam proyek tersebut, kehilangan kemandirian ekonomi yang dulu mereka miliki. Mereka kini bergantung pada sistem upah yang dikendalikan oleh perusahaan. Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut Bernstein sebagai “proletarisasi petani” — proses ketika kaum tani dipaksa meninggalkan alat produksinya dan menjadi tenaga kerja upahan dalam sistem kapitalis.
Dengan demikian, proyek energi geotermal di Halmahera Barat bukan hanya persoalan teknis pembangunan, melainkan bagian dari proses transformasi sosial-ekonomi yang menyingkirkan masyarakat lokal dari ruang hidupnya.
Perampasan Lahan dan Krisis Ekologis
Perampasan lahan atau land grabbing tidak selalu berarti pengambilalihan tanah secara paksa. Ia bisa hadir dalam bentuk kebijakan yang tampak legal dan modern: penerbitan izin investasi, pengalihan fungsi hutan, atau penetapan wilayah industri strategis. Dalam kasus Halmahera Barat, proyek geotermal sering kali disertai dengan dalih “kepentingan umum” dan “pembangunan berkelanjutan”. Akan tetapi, realitas sosialnya menunjukkan terjadinya ketimpangan akses terhadap sumber daya.
Tanah yang selama ini dikelola secara kolektif oleh masyarakat adat dan petani kini menjadi milik negara atau korporasi energi. Warga kehilangan hak adat dan kehilangan ruang ritual yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Padahal, bagi masyarakat Halmahera, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang spiritual yang mengikat hubungan manusia dengan leluhur dan alam.
Selain aspek sosial, eksplorasi geotermal juga memunculkan risiko ekologis serius. Pembukaan hutan untuk jalur eksplorasi menyebabkan erosi, hilangnya vegetasi, serta berkurangnya debit sumber air. Limbah panas dan zat kimia dari proses pengeboran dapat mencemari tanah dan air tanah seperti di Talaga Rano yang juga masuk diarea pencaplokan. Situasi ini menimbulkan ironi: proyek yang diklaim ramah lingkungan justru merusak ekosistem lokal yang selama ini dijaga masyarakat.
Energi, Kekuasaan, dan Ketimpangan Struktural
Konflik di Halmahera Barat memperlihatkan ketimpangan struktural yang mencolok antara aktor besar dan masyarakat kecil. Negara dan perusahaan memegang kendali atas perizinan, informasi, dan modal, sementara warga lokal tidak memiliki kekuatan politik untuk menentukan nasibnya. Dalam banyak kasus, konsultasi publik yang dilakukan hanya bersifat formalitas.
Henry Bernstein menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalisme global, pola relasi antara pusat dan pinggiran terus direproduksi: pusat menjadi tempat akumulasi modal dan pengambilan keputusan, sedangkan pinggiran menjadi sumber bahan baku, tenaga kerja murah, dan lahan eksploitasi. Halmahera Barat menjadi contoh nyata dari logika ini—sebuah daerah kaya sumber daya, namun hasilnya justru mengalir ke luar wilayah.
Pertanyaan “energi untuk siapa?” menjadi sangat relevan ketika melihat bahwa masyarakat yang menanggung dampak sosial-ekologis tidak mendapatkan akses yang setara terhadap manfaat proyek tersebut. Banyak desa di sekitar area geotermal masih kekurangan listrik, sementara panas bumi dari tanah mereka digunakan untuk menggerakkan industri di kota besar.
Kapitalisme Hijau sebagai Kolonialisme Baru
Fenomena eksploitasi energi di Halmahera Barat menunjukkan bahwa kapitalisme hijau tidak jauh berbeda dari kolonialisme klasik. Hanya saja, jika dahulu penjajahan dilakukan dengan senjata dan kekerasan, kini dilakukan melalui kebijakan, regulasi, dan investasi. Negara-negara maju mendorong agenda transisi energi di negara berkembang sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, tetapi di sisi lain mereka menjadi penerima manfaat terbesar dari rantai pasok energi bersih ini.
Dalam kerangka analisis Bernstein, hubungan ini disebut sebagai imperialisme agraria baru, di mana negara-negara pinggiran dipaksa menjadi penyedia sumber daya alam bagi pasar global. Energi panas bumi, yang seharusnya menjadi sumber kemandirian lokal, akhirnya hanya menjadi bagian dari mekanisme akumulasi kapital transnasional.
Maka, proyek energi hijau tidak bisa dipandang netral. Ia sarat dengan kepentingan politik-ekonomi global yang beroperasi atas nama keberlanjutan. Slogan-slogan seperti “net zero emission” atau “pembangunan berkelanjutan” sering kali menutupi praktik perampasan ruang hidup masyarakat adat dan petani kecil di lapangan.
Menuju Transisi Energi yang Adil
Menghadapi situasi ini, solusi yang dibutuhkan bukanlah penghentian proyek energi terbarukan, melainkan transformasi cara pandang dan tata kelola energi. Energi bersih seharusnya dibangun di atas prinsip keadilan sosial, ekologis, dan partisipatif. Artinya, masyarakat lokal harus dilibatkan secara penuh dalam setiap tahap—dari perencanaan, konsultasi, hingga pengelolaan manfaat ekonomi.
Konsep just energy transition (transisi energi yang adil) dapat menjadi kerangka baru untuk memperjuangkan keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan hak masyarakat lokal. Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek energi tidak menjadi instrumen perampasan, melainkan sarana pemberdayaan. Selain itu, hak atas tanah adat harus diakui melalui kebijakan agraria yang berpihak pada rakyat, bukan pada modal besar.
Sebagaimana diserukan oleh Bernstein, tanah dan sumber daya alam harus dipandang sebagai ruang kehidupan, bukan semata alat produksi. Dengan mengembalikan fungsi sosial tanah, energi hijau dapat benar-benar menjadi energi untuk rakyat—bukan hanya untuk pasar.
Penutup
Kasus perampasan lahan di Halmahera Barat membuka mata bahwa transisi menuju energi hijau tidak otomatis membawa keadilan. Di balik proyek yang disebut ramah lingkungan, tersimpan struktur kekuasaan yang masih timpang dan eksploitatif. Pertanyaan “energi untuk siapa?” adalah bentuk gugatan moral dan politik terhadap arah pembangunan yang lebih berpihak pada modal ketimbang manusia.
Kapitalisme hijau telah mengubah wajah eksploitasi, namun esensinya tetap sama: memperluas akumulasi modal dengan mengorbankan rakyat kecil dan alam. Oleh karena itu, perjuangan melawan perampasan lahan bukan hanya perjuangan lokal, tetapi bagian dari perlawanan global terhadap ketidakadilan ekologis dan ekonomi.
Energi sejati bukan sekadar daya listrik yang menggerakkan mesin, tetapi kekuatan yang menghidupkan manusia dalam keseimbangan dengan alam. Jika proyek energi hijau gagal menjawab keadilan itu, maka ia hanya akan menjadi topeng baru bagi kapitalisme lama yang masih memandang bumi dan manusia sebagai objek eksploitasi. Maka, pertanyaan itu kembali menggema di tanah Halmahera: energi untuk siapa? (*)

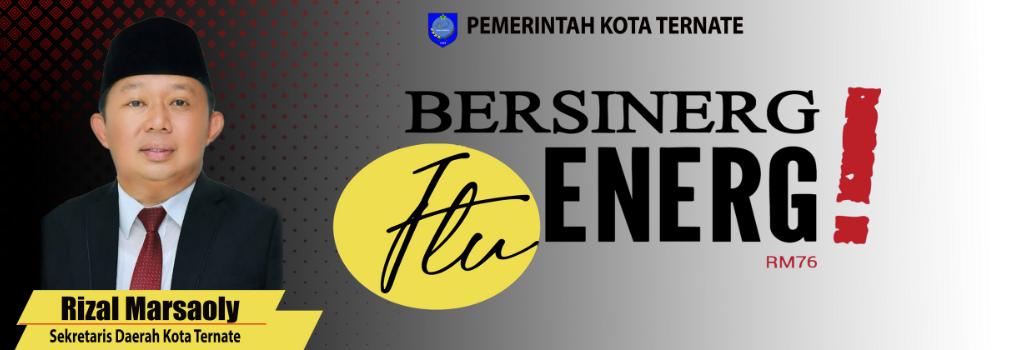












Komentar