Tambang Besi dan Luka Morotai

Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi “apa yang akan didapat?”, melainkan “apa yang akan tersisa?” setelah semua digali habis. Sebab ketika hutan musnah, laut rusak, dan tanah tandus, nilai besi yang diekspor tak sebanding dengan hilangnya kehidupan masyarakat.
Morotai bukan sekadar daratan kosong yang siap digarap. Ia adalah rumah bagi masyarakat di 88 desa yang memiliki ikatan spiritual dengan tanah, laut, dan hutan. Mereka menjaga wilayah leluhur bukan semata karena nilai ekonomi, melainkan demi budaya dan keberlanjutan hidup.
Tambang hanya akan merobek ruang hidup itu, satu per satu. Sejarah di berbagai daerah menunjukkan pola serupa: setelah perusahaan pergi, yang tersisa hanyalah tanah gersang, air tak layak minum, dan generasi yang kehilangan masa depan.
Ironi Morotai pun menjadi potret perlakuan negara terhadap wilayah pinggiran: menjadikannya ruang eksploitasi, bukan ruang kehidupan.
Di tengah krisis iklim global, semestinya kehadiran tambang menjadi alarm bahaya, bukan solusi pembangunan. Kekayaan sejati Morotai bukan terletak pada besi di perut bumi, melainkan pada kehidupan yang berakar dari tanah, laut, dan langitnya.
Pada masyarakat yang hidup dengan kearifan lokal. Pada keberlanjutan yang menjamin generasi berikutnya. Karena itu, masyarakat Morotai tidak menolak kemajuan, tetapi menolak bentuk kemajuan yang merampas tanah, laut, dan martabat mereka.
Prinsip hukum universal harus diingat: Salus Populi Suprema Lex Esto—Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai pelindung rakyat Morotai wajib mengambil sikap, menolak izin usaha pertambangan, dan berdiri bersama masyarakat demi masa depan Morotai yang hidup, bukan diperah. (*)

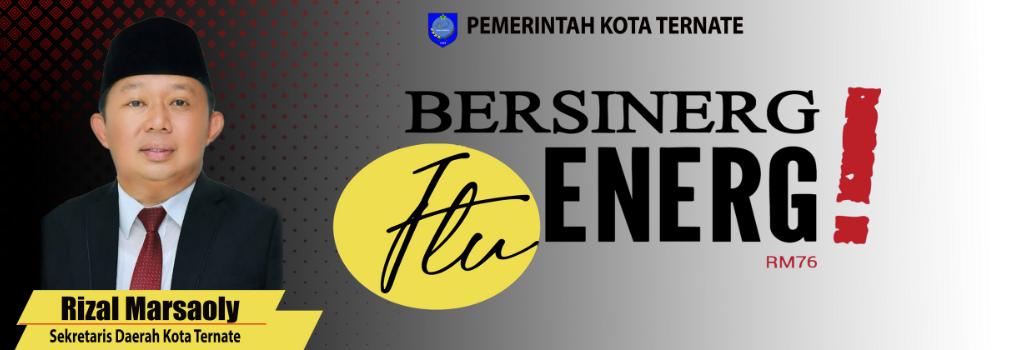












Komentar