Romantisme Sang Demonstran

Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Semakin sering kami bersama, semakin banyak yang kami bagi. Bukan hanya keluh kesah, tapi juga impian, harapan, dan keyakinan akan keadilan. Ia mulai ikut aksi. Awalnya hanya di barisan belakang, bersembunyi di balik poster. Tapi lambat laun, suaranya ikut lantang, teriakannya sekeras teriakanku. Ia bukan lagi Sinta yang ceroboh dan hanya sibuk dengan tugas kuliahnya. Ia berubah, menjadi Sinta yang tangguh, Sinta yang berani.
Suatu malam, setelah pulang dari aksi penolakan pembangunan pabrik baru di teluk, kami duduk di tepi pantai. Angin laut membelai wajah kami. Aku menatapnya. Wajahnya yang kelelahan, namun matanya tetap bersinar.
"Alfian," panggilnya lirih.
"Hmm?"
"Aku... aku mau jadi Sinta-mu, Alfian."
Jantungku berdebar tak keruan. Lidahku kelu. Aku hanya bisa menariknya ke dalam pelukanku. Dekat di dadaku, aku bisa merasakan detak jantungnya yang seirama dengan detak jantungku. Di tengah semerbak debu dan amis darah perjuangan, di tengah dentuman mesin-mesin penghancur, kami menemukan cinta. Bukan cinta yang manis layaknya kisah dongeng, tapi cinta juang. Cinta yang lahir dari kepedihan, tumbuh dari amarah, dan bersemi di atas harapan akan masa depan yang lebih baik.
Senja merona di ufuk barat, memudar perlahan digantikan bias jingga keunguan. Di tepi pantai, deburan ombak seolah menjadi melodi pengiring bisikan kami. Setelah pengakuan Sinta, kami terdiam, hanya suara napas dan detak jantung yang saling bersahutan. Aku mendekapnya lebih erat, seolah ingin menyerap setiap partikel kebahagiaan yang baru saja kudapatkan. Aroma rambutnya yang sedikit basah oleh embun laut dan keringat perjuangan, adalah wangi terindah yang pernah kuhirup.
"Sinta," bisikku, suaraku tercekat, "Kamu yakin?"
Ia mendongak, mata bulatnya menatapku lekat. Ada binar keyakinan di sana, sekaligus rona merah yang menjalar di pipinya.
“Sangat yakin, Alfian. Denganmu, semua terasa mungkin.”
Kami berbagi ciuman pertama, asin air mata dan manisnya janji yang tak terucap. Di tengah riuhnya deburan ombak dan bisikan angin, kami menemukan kedamaian yang tak pernah kubayangkan. Rasanya seperti bait-bait lagu Nadin Amizah yang sering kami dengar, “Berbisik pada bintang, tentang kita yang takkan pudar.”
Malam-malam setelah itu, kami kerap menghabiskan waktu di sebuah gubuk kecil di belakang kampus yang tak terpakai. Bukan sekadar bercengkrama, melainkan membangun impian. Kami memimpikan sebuah rumah dengan perpustakaan pribadi yang dindingnya penuh sesak buku, aroma kertas dan kopi selalu menyelimuti, menjadi saksi bisu setiap tawa dan diskusi kami. Sinta, dengan semangat membara, bahkan sudah membuat daftar buku-buku yang akan memenuhi rak-rak itu, dari koleksi lengkap Pramoedya Ananta Toer hingga buku-buku filsafat yang rumit.
“Nanti, kalau kita sudah punya rumah itu, kita baca buku bareng setiap malam,” ucapnya suatu hari, matanya berbinar seperti anak kecil.
“Terus, kalau ada kata-kata indah, kita tulis di dinding.”
Aku tersenyum, mengusap lembut pipinya.
“Dan kita akan punya kebun kecil di belakang, tempat kita menanam pohon-pohon endemik Halmahera. Mengembalikan sedikit dari yang sudah dirusak.”
Sinta mengangguk antusias.
“Dan setiap hari Minggu pagi, kita akan masak sarapan bersama. Aku akan buatkan kopi pahit kesukaanmu, tapi kali ini, tak ada ampasnya.”
Tawanya renyah, menghapus sejenak bayangan kata-kata ayahku yang menyakitkan. Kami merajut masa depan, tentang anak-anak yang akan kami besarkan dengan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang, tentang bagaimana kami akan terus berjuang untuk Halmahera, dan bagaimana kami akan selalu ada untuk Alda dan Arfandi.
Baca halaman selanjutnya ...

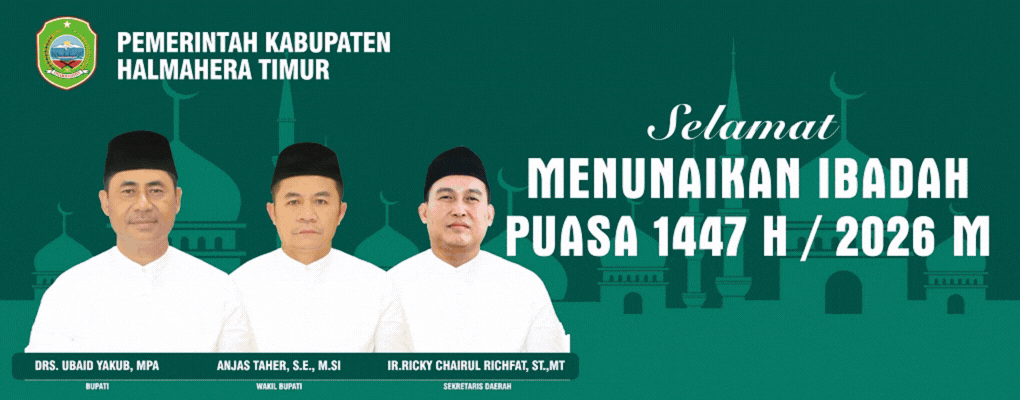












Komentar