Romantisme Sang Demonstran

Oleh: Jusri S. Jufri
(Koordinator Distrik Unkhair ll Samurai Maluku Utara)
Dalam kegetiran hidup, suara ayah bagai belati yang menusuk sukma, mengikis harga diri. Ia menyebutku sampah, ampas kopi pahit yang tak sudi diteguk. Sejak ibu pergi menghadap Ilahi pada penghujung dua ribu dua puluh satu, cercaan itu menjelma santapan pagiku. Ibu, satu-satunya insan yang memandangku sebagai manusia seutuhnya, kini hanya gundukan tanah basah di pemakaman kecil, di balik riuhnya kampung. Kepergiannya menorehkan luka menganga, perih tak terperi, terlebih saat kulihat Alda, kakak perempuanku, yang kini memikul peran ganda sebagai ibu dan kakak bagi Arfandi, adik laki-lakiku yang kurus kering dan selalu jadi sasaran amarah ibu tiri.
Kami bersemayam di Halmahera, pulau yang dulu rimbun menghijau, kini tercabik-cabik, menganga bak luka borok yang tak tersembuhkan. Korporasi nikel itu datang, menabur janji kesejahteraan, namun yang kami dapati hanya debu pekat, polusi mencekik, dan sungai yang keruh. Pohon-pohon raksasa, rumah bagi ribuan makhluk, kini hanya menyisakan tunggul-tunggul menyedihkan. Deru alat berat meraung setiap hari, membungkam kicauan burung, mengoyak ketenangan.
Aku, Alfian, sebuah nama yang ironis bagi hidupku yang selalu diliputi kelam, berusaha merengkuh pelarian dari realitas. Universitas Khairun di Ternate menjadi labuhan jiwaku. Fakultas Sastra Indonesia, di sanalah aku menemukan jati diri. Bukan di antara deretan angka dan rumus, melainkan di antara bait-bait puisi, di antara kisah-kisah perjuangan yang mengharu biru. Aku bergabung dengan Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI Malut). Di sanalah cakrawala pikirku terbuka. Kitab-kitab revolusioner yang tebal dan berbau apak menjelma sahabat setiaku. Marx, Lenin, Pramoedya, Tan Malaka—mereka berbisik padaku, meneriakkan keadilan yang selama ini hanya bisa kuraba dalam angan.
Setiap aksi, atau demonstrasi, adalah arena pelampiasan amarahku yang membuncah. Aku tak gentar pada pentungan Satpol PP, tak menggigil di bawah tatapan tajam polisi. Bagiku, mereka hanyalah bidak-bidak dalam permainan kotor para penguasa. Seringkali aku berhadap-hadapan dengan mereka, beradu argumen, saling dorong. Pernah, hidungku mengucurkan darah dihantam pentungan, namun perihnya tak seberapa dibanding luka di relung hatiku melihat kampung halaman yang terus dikeruk.
Di tengah riuhnya perjuangan itu, hadir ia. Sinta. Namanya secerah senyumnya, namun tingkahnya? Astaga, ia adalah bencana berjalan. Kecerobohannya tak terampuni. Pernah suatu kali, saat demonstrasi akbar, ia tersandung kakinya sendiri di hadapan barisan polisi, beruntung aku sigap menariknya. Ia cantik, imut, menggemaskan, dan manis. Rambutnya selalu sedikit berantakan, matanya berbinar-binar penuh penasaran, dan tawanya renyah bagai kerupuk. Mulanya, ia hanyalah teman curhatku. Tentang ayahku yang gemar menenggak miras, ibu tiriku yang kejam, tentang Alda dan Arfandi yang kian kurus. Ia mendengarkan segala keluh kesahku tanpa menghakimi, tanpa memberi saran klise. Hanya ada tatapan empati dan kadang, sentuhan lembut di lenganku yang membuatku merasa, untuk pertama kalinya, tidak sendirian.
"Gila, Yan, kamu tuh kenapa nekat banget sih?" ucapnya suatu hari, setelah aku berhasil lolos dari kepungan polisi. Napasnya terengah, wajahnya memerah karena berlari.
"Kalo nggak gini, siapa lagi yang bakal teriak, Sin? Hutan kita nangis, Sin. Sungai kita nangis. Mereka cuma diem, cuma liat uang. Gila, kan?" kataku, memandang jauh ke arah Halmahera yang tampak suram dari kejauhan.
Baca halaman selanjutnya ...

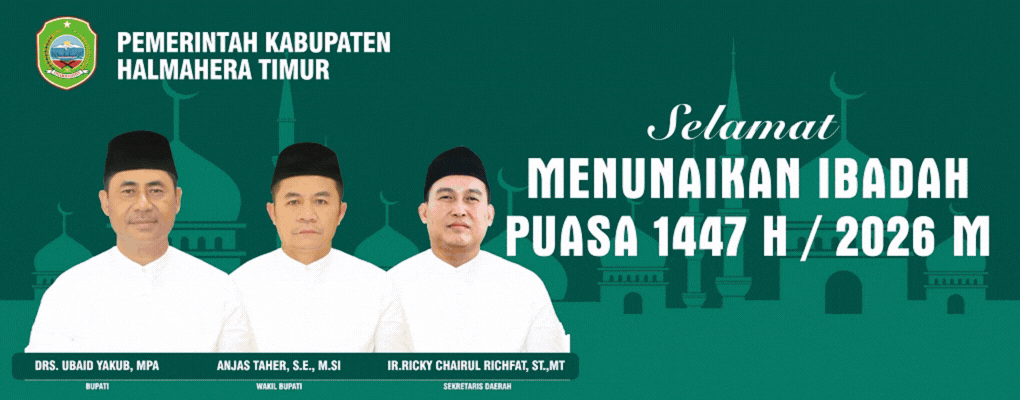












Komentar