“Suara Korban dan Kendala Implementasi UU TPKS di Lapangan”
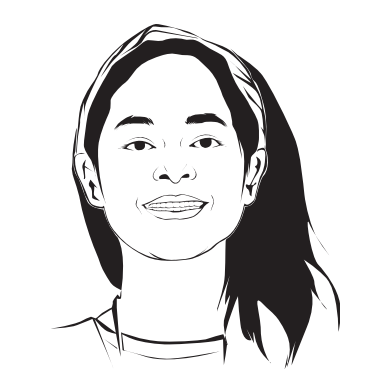
Oleh: Steffi Graf Gabi
(Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP GAMKI)
Kabar baik yang diterima oleh segenap masyarakat Indonesia atas disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Mei 2022 lalu kini telah berusia 2 tahun. Tidak sampai di situ, kabar baik tersebut menuntut semua pihak untuk terus mengontrol proses implementasinya di lapangan.
Ada harapan besar proses penanganan dan penegakan hukum menjadi “terbantu” dengan kehadiran UU TPKS ini karena mengatur lebih detail mengenai jenis kekerasan seksual hingga hak-hak korban. Pun, membuka peluang untuk mengusut kasus minim bukti fisik yang sebelumnya tidak diatur dalam UU ITE dan pornografi bahkan yang disyaratkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Nyatanya, hingga saat ini keluhan datang dari berbagai pihak baik aktivis, pendamping, korban maupun keluarga korban terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Banyak korban sadar akan kasus kekerasan seksual yang dialami tetapi enggan untuk melapor karena merasa keberhasilan nampaknya tidak akan berpihak kepada korban, dengan kata lain korban akan tetap kalah.
Deretan data dan fakta mengenai penanganan dan penegakan hukum kasus kekerasan seksual cukup memprihatinkan. Kasus di Palangkara misalnya, seorang polisi yang terbukti melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur divonis 2 bulan penjara, padahal jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara (Kompas.id, Borneo.co.id).
Adapun beberapa kasus yang telah dilaporkan ke kepolisian mengalami kemandekan dan tidak memberikan kejelasan ataupun keadilan bagi korban, antara lain dugaan kasus kekerasan seksual oleh musisi VS terhadap mahasiswi MT yang telah dilaporkan sejak Maret 2023 di Polres Ternate (KabarHalmahera.com).
Kasus kekerasan seksual terhadap 29 santriwati di sebuah pondok pesantren di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 hingga kini masih belum diproses ke pengadilan lantaran jaksa menilai kekurangan bukti (Kompas.com, Republika.co.id).
Kasus pelecehan dan kekerasan seksual tampak sangat sulit diperjuangkan hingga ke meja persidangan. Minimnya alat bukti menjadi alasan klasik aparat penegak hukum atas mandeknya proses hukum kasus kekerasan seksual.
Keterbatasan bukti awal seperti laporan korban, keluarga dan pengakuan pelaku menjadi faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Alasan ini pula yang kerapkali dikedepankan atas dihentikannya penyidikan dan penyelidikan kasus kekerasan seksual (Putra dan Dharmajaya, 2022), sungguh kenyataan yang memilukan hati korban.
Padahal UU TPKS jelas menyebutkan 9 jenis kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksanaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini berarti bahwa menyentuh saja bagian tubuh tertentu seseorang tanpa persetujuan itu pelecehan, apalagi mengusap hingga sampai pemaksaan perkosaan dan terjadinya perkosaan.
Lagipula, pasal 24 dan 25 UU TPKS mengakomodasi alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sebagai alat bukti yang sah, yaitu 1 (satu) keterangan korban ditambah 1 (satu) surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa itu cukup mentersangkakan dan menjerat terduga pelaku.
Dalam soal pemenuhan hak korban, hal pertama yang harus diperhatikan dalam konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana adalah esensi kerugian yang diderita korban. Yang mana esensi tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik semata tetapi juga memperhatikan aspek psikologis.
Hak korban berupa upaya pemulihan korban sedapat mungkin dikembalikan pada kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Selain itu, hak restitusi adalah hak korban kekerasan seksual yang semestinya ia peroleh sebagai biaya ganti rugi pelaku atas tidak pidana yang dilakukan.
Baca Halaman Selanjutnya..













Komentar