Setelah Balanda Pergi, Datanglah Tambang: Politik Pascakolonial di Bumi Halmahera

MEMULAI tulisan ini, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Halmahera Tengah. Tanah yang tak hanya menyimpan keindahan alam dan kekayaan sumber daya, tetapi juga sejarah panjang perjuangan dan keteguhan warganya dalam menghadapi perubahan zaman.
Maka tulisan ini hadir sebagai refleksi, bukan untuk menafikan capaian pembangunan, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap kebijakan ekonomi dan setiap proyek industri selalu membawa konsekuensi sosial dan ekologis. Dengan semangat peringatan ulang tahun Halmahera Tengah, mari kita menengok sejenak ke belakang, ke sejarah yang panjang, untuk memahami bagaimana kolonialisme lama belum benar-benar pergi, ia hanya berganti rupa, dari rempah ke nikel, dari penaklukan bersenjata ke penaklukan lewat kebijakan.
Kolonialisme di Indonesia secara formal telah berakhir pada 1945, tetapi relasi kekuasaan yang dibangun oleh kolonialisme tidak ikut lenyap bersama pengusiran Belanda. Ia terus hidup dalam bentuk yang lebih halus melalui kebijakan pembangunan. Di Halmahera, warisan kolonialisme itu menemukan bentuk barunya dalam industri tambang. Bila dahulu rempah menjadi alasan ekspedisi dan penaklukan, kini nikel memainkan peran yang sama, menjadi komoditas global yang menjerat masyarakat lokal dalam jaringan kapitalisme dunia.
Dalam logika kolonial lama, wilayah-wilayah di pinggiran selalu dilihat sebagai ruang sumber daya, bukan ruang kehidupan. Pandangan ini tetap bertahan sampai hari ini, sebagaimana ditunjukkan oleh proyek-proyek pertambangan di Halmahera Tengah, Timur, Utara dan Selatan. Negara dan korporasi menempatkan tanah, hutan, dan laut sebagai aset produktif yang harus dieksploitasi demi kepentingan nasional. Di balik jargon hilirisasi dan transisi energi bersih, terdapat struktur kekuasaan yang meniru pola kolonial yakni tanah masyarakat diambil atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), dan masyarakat lokal disulap menjadi buruh tambang dalam rantai produksi global.
Edward Said (1978) dalam Orientalism menyebut bahwa kolonialisme bekerja bukan hanya melalui kekerasan fisik, tetapi melalui representasi. Dunia Timur, katanya, selalu digambarkan sebagai terbelakang agar Barat merasa sah mengintervensinya. Pola representasi serupa kini dijalankan negara terhadap masyarakat Halmahera, mereka diposisikan sebagai masyarakat yang “menunggu pembangunan”. Kehadiran tambang dijustifikasi sebagai jalan menuju kemajuan, meski bagi warga setempat, kemajuan itu berarti kehilangan lahan, rusaknya sungai, dan hancurnya sistem pertanian.
Data dari Forest Watch Indonesia (2023) menunjukkan bahwa di Kabupaten Halmahera Tengah terdapat 66 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi mencapai 142.964 hektare, atau hampir 60 persen dari luas daratan kabupaten tersebutdan belum di kabupaten kota yang lain. Banyak di antara izin itu tumpang tindih dengan wilayah hutan lindung dan tanah adat masyarakat Sawai. Proses perizinan yang kompleks sering kali tidak disertai konsultasi yang baik dengan warga. Hasilnya, masyarakat seperti di Lelilef, Gemaf, dan Sageakehilangan ruang hidup yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Tania Murray Li (2007) menjelaskan dalam konsep the will toimprove bahwa negara kerap membungkus proyek dominasi dengan retorika kesejahteraan. Ia menyebut, di banyak kasus pembangunan, masyarakat lokal dianggap “tidak efisien” sehingga harus “diperbaiki” melalui intervensi teknokratis. Hal yang sama terjadi di Halmahera. Pembangunan tambang nikel dan kawasan industri IWIP dijadikan simbol modernisasi. Tetapi masyarakat lokal jarang memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan itu. Mereka lebih sering menjadi penonton di tanah sendiri, menerima kompensasi yang tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka alami.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana kolonialisme baru bekerja. Bila pada masa VOC penjajahan dilakukan dengan kekuatan senjata, kini kekuasaan bekerja melalui kontrak investasi dan kebijakan negara. Bagi Hiariej, negara modern justru sering kali menjadi komprador kapital global. Alih-alih menyejahterakan, negara justru berfungsi sebagai fasilitator bagi korporasi multinasional. Menyediakan tanah murah, tenaga kerja yang dapat dieksploitasi, dan jaminan hukum bagi investasi asing. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah pusat dan daerah menyesuaikan tata ruang dan perizinan demi memperlancar investasi industri nikel di Teluk Weda. Dalam perspektif pascakolonial, praktik ini merupakan bentuk dominasi yang dilembagakan, di mana hukum dan birokrasi menjadi instrumen penjajahan baru.
Bagi masyarakat Halmahera, perubahan itu bukan hanya ekonomi, tetapi juga kultural dan ekologis. Struktur sosial yang sebelumnya relatif egaliter berubah menjadi hirarkis. Muncul elite-elite lokal yang menjadi perantara antara perusahaan dan warga, memanfaatkan kedekatan dengan birokrasi untuk menguasai sumber kompensasi dan proyek. Di sisi lain, banyak warga yang dulunya petani atau nelayan kini menjadi buruh kontrak di perusahaan tambang dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak stabil. Inilah yang disebut Gayatri Spivak (1988) sebagai posisi subaltern kelompok yang tidak hanya dipinggirkan secara ekonomi, tetapi juga kehilangan suara politik dan representasi. Mereka menjadi objek kebijakan yang tidak pernah sepenuhnya mampu berbicara atas dirinya sendiri.
Dampak ekologis yang dihadapi masyarakat Halmahera memperkuat dimensi pascakolonial ini. Laporan MongabayIndonesia (2022) menunjukkan deforestasi besar-besaran di kawasan hutan Halmahera akibat ekspansi tambang nikel. Hutan yang sebelumnya menjadi sumber pangan dan air masyarakat kini berubah menjadi wilayah gersang. Di beberapa desa, air sungai tercemar, hasil pertanian menurun, dan kasus penyakit kulit meningkat. Tubuh masyarakat lokal menanggung beban ekologis dari proyek yang konon membawa “transisi energi bersih” bagi dunia. Ironisnya, mereka yang hidup di daerah penghasil nikel tidak menikmati listrik atau air bersih yang layak.
Dalam konteks ini, pembangunan tidak sekadar soal kemajuan ekonomi, tetapi tentang siapa yang berkuasa menentukan makna kemajuan itu. Negara dan perusahaan membangun narasi tunggal tentang pembangunan dan kesejahteraan, sementara pengalaman masyarakat lokal dihapus dari wacana resmi. Antropologi pascakolonial mengingatkan bahwa yang paling penting bukan hanya menolak kolonialisme lama, tetapi juga membongkar bagaimana pengetahuan dan bahasa pembangunan terus mereproduksi ketimpangan.
Membaca Halmahera dari kacamata pascakolonial berarti menyadari bahwa kolonialisme tidak benar-benar pergi, ia hanya berganti kulit. Kini, penjajahnya tidak datang dengan kapal perang, tetapi dengan kontrak investasi dan janji hilirisasi. Negara yang dulu berjuang melawan kolonialisme kini menjadi bagian dari struktur global yang mengekstraksi sumber daya dan tenaga rakyatnya sendiri. Di balik jargon “kedaulatan industri” terselip fakta bahwa hasil tambang dikirim untuk memenuhi kebutuhan energi negara lain, sementara masyarakat lokal masih berjuang mempertahankan hidup dari tanah yang kian sempit.
Setelah Balanda pigi, tambang datang. Ia membawa wajah baru kekuasaan yang tidak lagi berbendera asing, tetapi tetap menundukkan yang lokal. Di Bumi Halmahera, sejarah kolonial tidak berakhir ia hanya berganti bentuk dari rempah ke nikel, dari gubernur jenderal ke direktur perusahaan, dari tanam paksa ke kontrak kerja. Dalam kerangka pascakolonial, yang berubah hanyalah bahasa dan alatnya, yang tetap sama adalah ketimpangan antara mereka yang mengambil dan mereka yang ditinggalkan.
Kemerdekaan, dalam pengertian ini, belum benar-benar terjadi. Ia masih harus diperjuangkan bukan dengan senjata, melainkan dengan kesadaran untuk mendekolonisasi cara kita memahami pembangunan. Hanya dengan mengembalikan suara masyarakat lokal, mengakui pengetahuan dan hak mereka atas ruang hidup, kita dapat mengatakan bahwa Halmahera telah benar-benar merdeka. Sebab selama tambang masih berdiri di atas penderitaan rakyatnya, sejarah kolonial itu akan terus berulang, hanya dengan nama yang berbeda.(*)

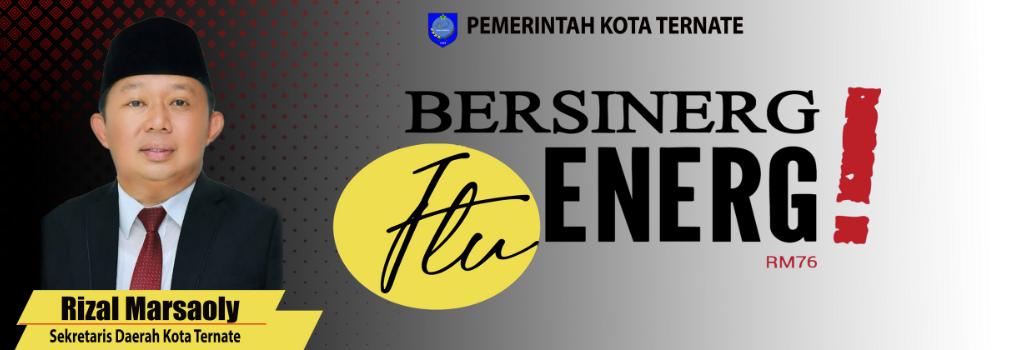













Komentar