Korupsi dalam Bayang-Bayang Penjajahan: Warisan Lama di Era Modern

KORUPSI bukanlah fenomena baru dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Jika ditelusuri lebih dalam, praktik korupsi sudah mengakar sejak masa penjajahan, baik di era kolonial Belanda maupun Jepang. Warisan kolonial ini kemudian membentuk pola relasi kuasa, mentalitas birokrasi, hingga struktur pemerintahan yang terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ironisnya, setelah lebih dari tujuh dekade merdeka, Indonesia belum sepenuhnya mampu membebaskan diri dari praktik-praktik koruptif yang diwariskan era penjajahan tersebut.
Tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana praktik korupsi pada masa kolonial meninggalkan jejak historis yang berkelanjutan hingga hari ini. Lebih dari sekadar menyalahkan masa lalu, tulisan ini juga mencoba merefleksikan bagaimana bangsa ini seharusnya menghadapi kenyataan bahwa sebagian dari krisis integritas dan moral birokrasi di masa kini memiliki akar sejarah yang panjang.
Korupsi di Era Penjajahan: Praktik Sistemik dalam Pemerintahan Kolonial
Pada masa Hindia Belanda, korupsi bukan hanya terjadi di level bawah atau oknum pejabat tertentu, melainkan menjadi bagian dari sistem pemerintahan itu sendiri. VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), sebagai perusahaan dagang yang memerintah Nusantara selama lebih dari dua abad, terkenal dengan julukan "perusahaan dagang korup pertama di dunia". Di balik dominasi dagang dan kekuatan militer VOC, tersembunyi praktik-praktik penyuapan, manipulasi laporan, penggelapan kekayaan, dan pemerasan terhadap rakyat.
Prajurit VOC yang ditempatkan di daerah-daerah jajahan diberi kebebasan untuk "menghidupi dirinya sendiri" dengan cara memungut pajak, menjual izin, atau memanfaatkan posisi kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam struktur seperti ini, korupsi menjadi alat untuk bertahan hidup sekaligus memperkaya diri. Praktik tersebut semakin diperparah dengan tidak adanya sistem akuntabilitas yang kuat dalam birokrasi kolonial. Kekuasaan cenderung bersifat absolut, dan laporan ke pusat pemerintahan di Belanda sering kali dimanipulasi.
Ketika VOC bubar dan pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan secara langsung, korupsi tidak serta-merta menghilang. Sebaliknya, praktik-praktik itu semakin terinstitusionalisasi. Para bupati pribumi yang ditunjuk sebagai perpanjangan tangan pemerintahan kolonial diberi kewenangan besar tanpa pengawasan ketat. Mereka memungut pajak seenaknya, melakukan kerja paksa, dan mengambil bagian dari hasil panen petani. Mentalitas feodal dalam struktur kekuasaan memperkuat watak patronase dan praktik gratifikasi. Korupsi menjadi bagian dari relasi kekuasaan yang dianggap normal.
Korupsi di Era Jepang: Peralihan Kekuasaan, Tapi Bukan Perubahan Moral
Ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada 1942, sistem pemerintahan berubah drastis, tetapi praktik korupsi tetap berlangsung. Di satu sisi, Jepang membubarkan banyak struktur kolonial lama dan mempropagandakan semangat kebangsaan Asia. Namun di sisi lain, kebutuhan perang dan tekanan ekonomi membuat pemerintahan Jepang justru mendorong eksploitasi sumber daya secara besar-besaran, yang dalam praktiknya membuka ruang korupsi baru.
Para pejabat lokal diberi tugas untuk mengelola distribusi logistik, pengumpulan hasil bumi, dan mobilisasi tenaga kerja romusha. Dalam situasi seperti ini, terjadi praktik penimbunan, manipulasi distribusi, dan pengambilan keuntungan pribadi di tengah penderitaan rakyat. Kekacauan administratif, tekanan militer, dan lemahnya kontrol terhadap aparat lokal menjadikan korupsi tetap hidup dan bersembunyi di balik euforia perlawanan terhadap kolonialisme Barat.
Warisan Penjajahan dalam Praktik Korupsi Pasca-Kemerdekaan
Indonesia merdeka pada tahun 1945, tetapi kebebasan itu tidak serta-merta membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu sebabnya adalah karena sistem birokrasi yang digunakan adalah warisan kolonial. Banyak aparat pemerintah yang berasal dari struktur kolonial tetap dipertahankan karena alasan keterbatasan sumber daya manusia. Dengan demikian, mentalitas dan praktik kolonial ikut terbawa ke dalam sistem pemerintahan baru.
Pola relasi kuasa berbasis patron-klien, birokrasi yang tidak transparan, serta budaya "asal atasan senang" terus berlangsung bahkan dalam rezim-rezim nasionalis sekalipun. Di era Orde Lama, meskipun semangat revolusi dan retorika nasionalisme begitu kuat, persoalan korupsi sudah mulai menjadi perhatian. Presiden Soekarno sendiri pernah menyebut korupsi sebagai "penyakit mental" dan membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) pada 1957 untuk memberantas korupsi. Namun, usaha ini tidak berumur panjang dan gagal membawa dampak signifikan.
Ketika Orde Baru berkuasa di bawah Soeharto, korupsi mencapai tingkat yang sangat sistemik dan meluas. Dengan dalih pembangunan, rezim ini menciptakan apa yang disebut oleh banyak pengamat sebagai “korupsi yang terorganisir”. Para pejabat dan kroni penguasa menjadikan jabatan sebagai ladang ekonomi. Pemerintahan yang bersifat sentralistik dan kontrol politik yang otoriter membuat pengawasan terhadap praktik korupsi menjadi lemah. Menurut Transparency International, pada akhir Orde Baru, Indonesia termasuk salah satu negara paling korup di dunia.
Budaya Feodal dan Warisan Mentalitas Kolonial
Salah satu warisan paling berbahaya dari masa penjajahan adalah budaya kekuasaan yang bersifat feodal dan hierarkis. Dalam budaya seperti ini, pemimpin dianggap sebagai sosok yang tidak boleh dikritik, bahkan cenderung dipuja. Hal ini menciptakan relasi yang timpang antara rakyat dan pemerintah. Dalam sistem seperti ini, kritik terhadap pejabat bisa dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas atau bahkan dianggap tidak sopan.
Budaya semacam ini memupuk suburnya praktik gratifikasi, suap, dan nepotisme. Rakyat tidak lagi melihat aparat sebagai pelayan publik, tetapi sebagai pihak yang harus “dihormati” agar mendapat pelayanan. Para pejabat pun tidak melihat jabatan sebagai amanah, tetapi sebagai privilege yang memberi peluang untuk memperkaya diri. Dalam konteks ini, korupsi menjadi bagian dari budaya birokrasi yang sudah berlangsung turun-temurun.
Dampak Sistemik Korupsi: Kemiskinan dan Ketimpangan
Korupsi bukan sekadar tindakan menyimpang dari hukum, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran negara diselewengkan, maka kualitas pelayanan publik menurun. Pembangunan menjadi lamban, infrastruktur rusak, pendidikan tidak merata, dan layanan kesehatan tidak optimal. Di daerah-daerah yang kaya sumber daya, korupsi justru memperparah kemiskinan karena kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir elite.
Ketimpangan sosial-ekonomi yang mencolok di Indonesia hari ini sebagian besar disebabkan oleh praktik korupsi yang kronis. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, peningkatan mutu pendidikan, atau program pengentasan kemiskinan, justru berakhir di rekening pribadi pejabat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi negara menurun. Demokrasi menjadi kehilangan makna ketika yang duduk di kursi kekuasaan adalah mereka yang mengandalkan uang, bukan integritas dan kapasitas.
Perlawanan terhadap Korupsi: Peluang dan Tantangan
Sejak era Reformasi, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi birokrasi, transparansi anggaran, hingga penguatan partisipasi masyarakat sipil. Namun perjuangan ini masih menghadapi banyak tantangan. Di satu sisi, ada kemajuan yang patut diapresiasi seperti keberhasilan penangkapan sejumlah pejabat tinggi. Namun di sisi lain, masih banyak celah hukum, intervensi politik, dan resistensi dari dalam sistem yang membuat upaya pemberantasan korupsi berjalan lambat.
KPK, sebagai lembaga antikorupsi, juga mengalami dinamika politik yang tidak mudah. Perubahan UU KPK, pelemahan wewenang, dan kriminalisasi terhadap penyidik menunjukkan bahwa perlawanan terhadap korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga pertarungan politik. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku korupsi justru kembali mendapatkan jabatan politik setelah keluar dari penjara, menunjukkan rendahnya standar etika dalam sistem politik kita.
Menghapus Warisan Lama: Revolusi Mental dan Pendidikan Antikorupsi
Untuk menghentikan siklus korupsi yang diwariskan sejak masa penjajahan, Indonesia memerlukan perubahan mendasar yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Revolusi mental yang selama ini hanya menjadi slogan harus dihidupkan melalui pendidikan antikorupsi yang dimulai sejak usia dini. Sekolah tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga integritas, empati, dan tanggung jawab sosial.
Di sisi lain, pembenahan sistem birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh. Digitalisasi layanan publik, transparansi anggaran, dan sistem pengawasan yang ketat perlu diperluas hingga ke tingkat desa. Para pejabat publik harus diberikan pelatihan etika pemerintahan dan diberi sanksi tegas ketika melanggar aturan. Tanpa tindakan konkret, sejarah kolonial korupsi hanya akan terus berulang dalam bentuk yang lebih canggih.(*)

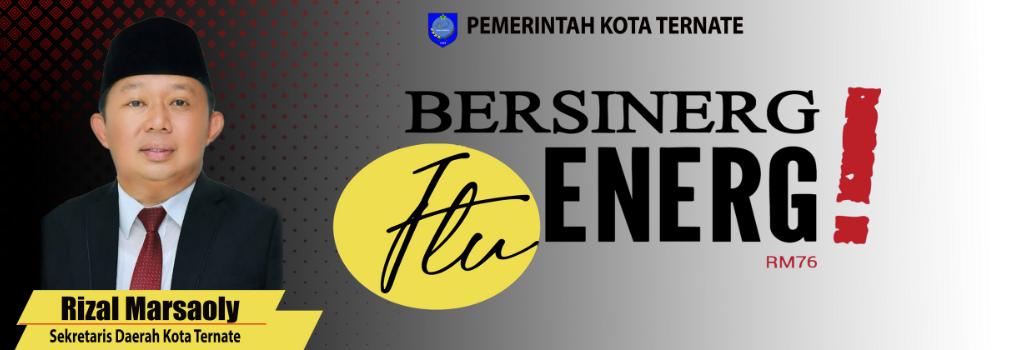








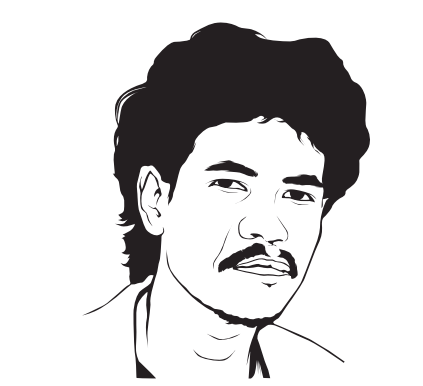
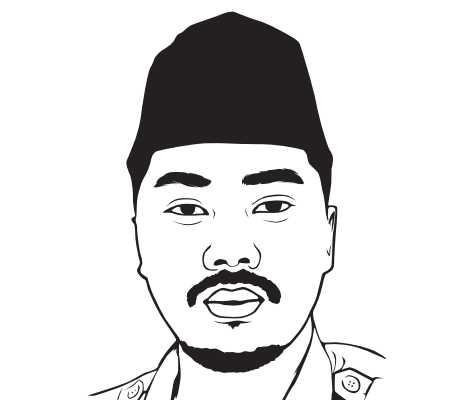


Komentar