Implementasi Pendidikan Inklusif, Antara Paradigma Humanistik dan Realitas Struktural

Oleh: Bachtiar S. Malawat
(Mahasiswa Pendidikan IPA Unutara)
Pendidikan inklusif telah menjadi salah satu wacana penting dalam diskursus pendidikan global maupun nasional. Wacana ini didorong oleh semangat humanisme dan keadilan sosial, yang menempatkan setiap manusia sebagai subjek yang berhak atas pendidikan, terlepas dari kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, atau kulturalnya.
Dalam konteks ini, pendidikan inklusif tidak hanya berbicara tentang akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi lebih luas lagi, sebuah sistem yang mengakomodasi keberagaman dan menolak segala bentuk diskriminasi.
Baca Juga: PENDIDIKAN INDONESIA: Habis Gelap Terbitlah Gelap
Namun, idealisme yang melandasi pendidikan inklusif justru bertabrakan dengan realitas struktural di lapangan, yang sarat dengan ketimpangan, birokratisasi pendidikan, hingga kekerasan simbolik dalam praktik institusional.
Secara normatif, pendidikan inklusif dibangun atas fondasi paradigma humanistik. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, memiliki potensi, dan harus difasilitasi untuk berkembang secara utuh.
Dalam buku Teori-Teori Pendidikan karya Nuraini Sayomukti, dijelaskan bahwa pendekatan humanistik dalam pendidikan bertumpu pada pengakuan terhadap keunikan individu, penghargaan terhadap kebebasan belajar, serta penciptaan ruang yang kondusif bagi pertumbuhan psikologis dan sosial peserta didik.
Baca Juga: Koran Digital Malut Post Edisi 15 Juli 2025
Sayangnya, implementasi di lapangan sering kali berjalan dalam ruang yang rigid, birokratis, dan berorientasi pada hasil belajar semu yang terukur secara numerik, bukan perkembangan manusia secara menyeluruh.
Hal ini menegaskan adanya jarak epistemologis sekaligus praksis antara wacana humanistik dan realitas pendidikan inklusif di Indonesia.
Baca Halaman Selanjutnya..

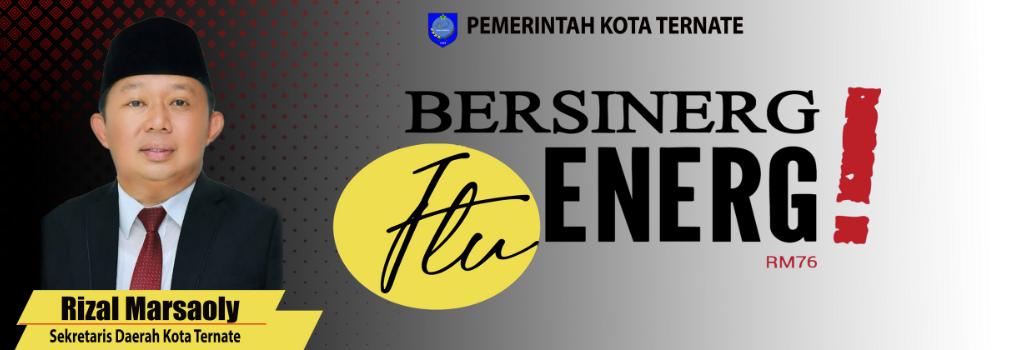










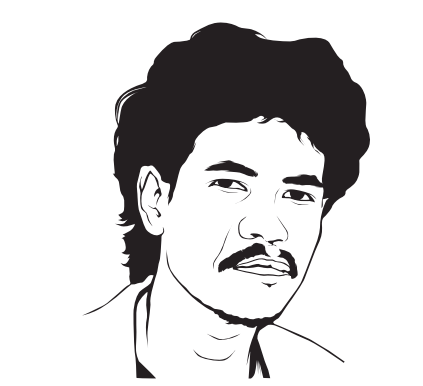
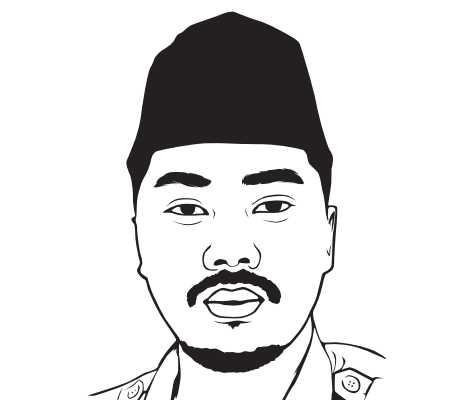
Komentar